Pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata siap beroperasi
)
Pembangkit listrik tenaga surya terapung (PLTS) Cirata yang terletak di Waduk Cirata, Jawa Barat, dengan kapasitas 145 MW (ac) atau 195 MW (p) telah diresmikan. Acara ini menandai tonggak sejarah penting bagi Indonesia karena kini Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga surya terapung terbesar di Asia Tenggara, melampaui pembangkit listrik tenaga surya terapung Tengeh di Singapura.
Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa beroperasinya PLTS terapung Cirata merupakan sebuah pencapaian yang signifikan dalam percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya skala besar di Indonesia. Pengembangan tenaga surya di Indonesia hampir tidak ada sejak tahun 2020. Namun, biaya investasi PLTS yang terus menurun telah menjadikannya sebagai sumber energi terbarukan yang paling murah. Oleh karena itu, Indonesia harus mengoptimalkan potensi teknis PLTS yang mencapai 3,7 TWp hingga 20 TWp untuk mendukung pencapaian target emisi puncak sektor listrik pada tahun 2030 dengan biaya serendah mungkin.
IESR juga mendorong pemerintah dan PLN untuk memanfaatkan potensi teknis PLTS terapung yang mencapai 28,4 GW dari 783 lokasi perairan di Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan PLTS. Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan bahwa terdapat potensi PLTS terapung skala besar yang dapat dikembangkan di setidaknya 27 lokasi perairan yang memiliki pembangkit listrik tenaga air (PLTA), dengan total potensi 4,8 GW dan nilai investasi setara USD 3,84 miliar (Rp 55,15 triliun). Pemanfaatan potensi PLTS terapung ini akan mempercepat pencapaian target bauran energi terbarukan dan mencapai target net zero emission (NZE) lebih cepat dari tahun 2060.
Pemerintah dan Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus mengoptimalkan potensi pembangkit listrik tenaga surya terapung dengan menciptakan kerangka peraturan yang menarik bagi bisnis untuk berinvestasi di pembangkit ini. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan menawarkan tingkat pengembalian investasi yang menarik yang sesuai dengan profil risiko namun tetap menarik dan mengurangi beban tambahan.
Salah satu hal yang menjadi perhatian pemerintah adalah skema penugasan PLN kepada anak perusahaannya, yang telah menjadi pilihan prioritas untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya terapung. Melalui skema ini, anak perusahaan mencari investor ekuitas untuk kepemilikan minoritas namun harus bersedia menanggung porsi ekuitas yang lebih besar melalui pinjaman pemegang saham.
"Skema ini menguntungkan PLN namun mengurangi pengembalian investasi bagi investor dan berisiko terhadap bankabilitas proyek dan minat pemberi pinjaman. Skema ini juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha, karena hanya mereka yang memiliki modal besar yang dapat bermitra dengan PLN, dan sebagian besar investornya adalah investor asing. Hal ini dapat berdampak pada minat investasi secara keseluruhan," ujar Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa.
Solusinya, menurut Fabby, perlu dukungan pemerintah dengan memperkuat permodalan PLN dan anak perusahaannya melalui penyertaan modal negara (PMN) khusus untuk pengembangan energi terbarukan dan memberikan pinjaman konsesi kepada PLN melalui PT SMI, yang kemudian dapat dikonversi menjadi kepemilikan saham di proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung.
Indonesia dapat meraup potensi investasi dan listrik rendah emisi dari pembangkit listrik tenaga surya terapung dengan dukungan regulasi yang pasti dan mengikat dari pemerintah. Pada bulan Juli 2023, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan yang tidak lagi membatasi luas badan air di waduk yang dapat dimanfaatkan untuk PLTS terapung sebesar 5%. Peraturan tersebut membuka peluang pengembangan PLTS terapung dalam skala yang lebih besar, dengan catatan apabila menggunakan lebih dari 20% luas badan air, maka perlu mendapatkan rekomendasi dari Komisi Keamanan Bendungan.
Marlistya Citraningrum, Manajer Program Akses Energi Berkelanjutan, IESR, melihat hal ini sebagai peluang untuk mengatasi masalah lahan dalam mengembangkan PLTS.
"Ketersediaan lahan seringkali menjadi kendala dalam pengembangan PLTS, terutama di daerah yang sudah padat dengan harga tanah yang tinggi, serta tutupan lahan yang mungkin tidak sesuai untuk PLTS, misalnya lahan pertanian yang terlalu curam atau lahan pertanian yang masih produktif. Indonesia juga memiliki beberapa bendungan, baik PLTA maupun bukan, yang dapat digunakan sebagai lokasi potensial. Proyek Hijaunesia 2023, misalnya, telah menawarkan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya terapung di Gajah Mungkur, Kedung Ombo, dan Jatigede dengan kapasitas masing-masing 100 MW," kata Marlistya.
Namun, menurut Marlistya, secara keseluruhan perencanaan, tender, dan pembangunan PLTS terapung di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Meskipun merupakan proyek unggulan dan bentuk kerja sama antar pemerintah (G2G), jadwal penyelesaian PLTS terapung Cirata cukup panjang - dimulai dengan nota kesepahaman antara Indonesia dan Uni Emirat Arab pada tahun 2017 dan pembentukan perusahaan patungan antara PJB Investasi dan Masdar di tahun yang sama, penandatanganan PPA baru dilakukan pada tahun 2020 dan financial closing pada tahun 2021. Proses yang panjang ini mengurangi daya tarik investasi pembangkit listrik tenaga surya terapung di Indonesia.
Pengembangan rantai pasokan untuk komponen solar PV dan floating PV di Indonesia juga terbuka lebar, termasuk untuk sel surya dan modul. Tidak hanya untuk pasar domestik yang hingga kini belum mencapai 1 GW, sel surya dan modul dengan kriteria tier 1 yang diproduksi di Indonesia juga ditujukan untuk pasar luar negeri. Produsen sel surya dan modul tier 1 asal China, Trina Solar, telah bekerja sama dengan Sinarmas untuk membangun pabrik sel surya dan modul terintegrasi di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, dengan kapasitas produksi 1 GW/tahun.


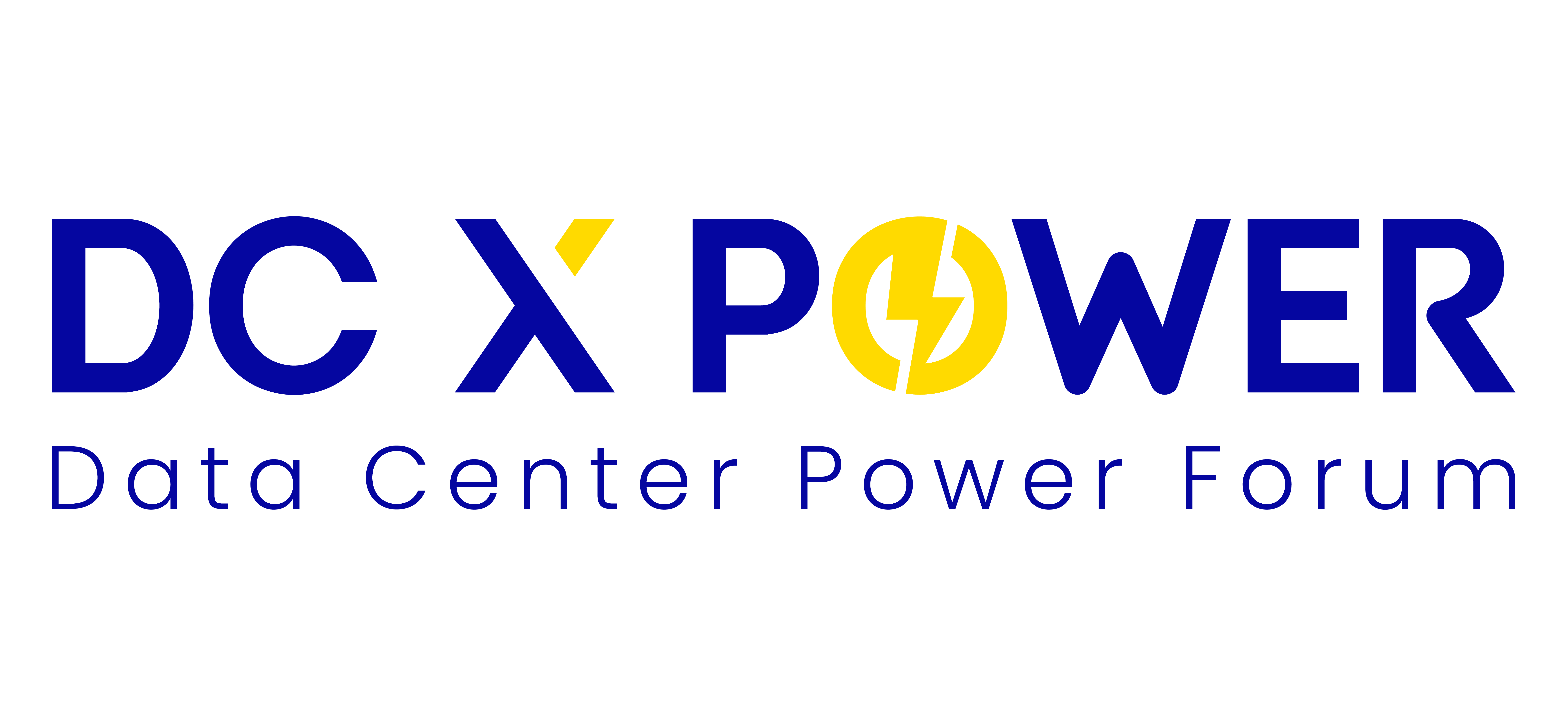
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

)
)
)